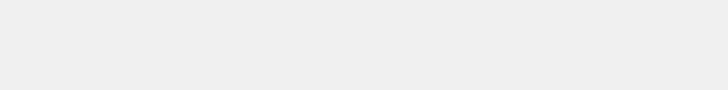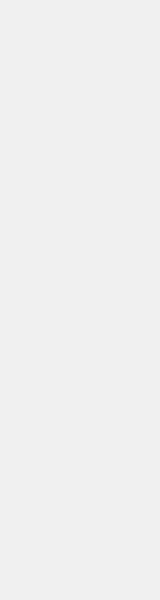Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tengah serius menangani puluhan anak yang terpapar ideologi kekerasan ekstrem, sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena pergeseran modus penyebarannya melalui ruang digital. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat setidaknya 112 anak di 26 provinsi terpapar paham radikal melalui media sosial dan permainan daring sepanjang tahun 2025. Sementara itu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi sedikitnya 70 anak di berbagai wilayah Indonesia terpapar ideologi Neo-Nazi, sebuah bentuk kekerasan ekstrem berbasis supremasi ras, yang menyusup melalui konten global.
Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan bahwa anak-anak yang terpapar paham radikalisme merupakan korban dari lingkungan dan sistem yang belum sepenuhnya aman, sehingga negara memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan memulihkan mereka. KPAI mengapresiasi kinerja Densus 88 dan BNPT dalam mengungkap praktik perekrutan ini, melihatnya sebagai upaya penyelamatan anak-anak Indonesia dari eksploitasi jaringan terorisme. Proses radikalisasi di era digital disebut jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional, di mana paparan paham radikal kini hanya membutuhkan waktu 3-6 bulan, dibanding 2-5 tahun sebelumnya. Kelompok radikal, termasuk simpatisan ISIS/Ansharuh Daulah, memanfaatkan kerentanan psikologis remaja, khususnya pada aspek emosi, perilaku, dan pola pikir. Pakar kriminologi dan Plt. Kasubdit Bina dalam Masyarakat BNPT RI, Dr. Ardi Putra Prasetya, menjelaskan bahwa anak-anak yang kesepian menjadi target empuk, di mana mereka diajak berbincang ringan dalam permainan daring, lalu secara perlahan diperkenalkan ideologi.
Fenomena ini semakin kompleks dengan ditemukannya puluhan anak yang terpapar ideologi kekerasan ekstrem melalui grup daring seperti "True Crime Community (TCC)". Rata-rata usia anak yang terpapar kini jauh lebih muda, sekitar 13 tahun, dengan usia terendah 10 tahun dan tertinggi 18 tahun, berbeda signifikan dari rata-rata pelaku terorisme periode 2014-2019 yang berkisar 28-35 tahun. Faktor kerentanan lainnya mencakup trauma emosional akibat perundungan (bullying) dan keluarga yang tidak utuh (broken home). Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menambahkan bahwa lebih dari 15 juta anak di Indonesia berpotensi mengalami kondisi tanpa ayah (fatherless) dan hampir 1,3 juta anak mengalami depresi, menjadikan mereka rawan dimanipulasi oleh kelompok radikal.
KPAI bersama BNPT dan kementerian/lembaga terkait berupaya optimal untuk memastikan anak-anak korban radikalisme tidak diproses secara pidana, melainkan difokuskan pada rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan penguatan lingkungan. Anggota KPAI, Dian Sasmita, menegaskan bahwa penanganan anak korban radikalisme termasuk kategori anak dengan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, sehingga harus berbasis intervensi sosial. Pendekatan non-pidana dinilai lebih tepat karena sistem peradilan pidana dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.
Langkah pencegahan yang ditekankan KPAI meliputi penguatan fungsi keluarga sebagai benteng utama, pengawasan aktif media sosial oleh orang tua, dan peningkatan literasi digital anak agar tidak mudah terjebak propaganda ekstrem. Di lingkungan sekolah, KPAI merekomendasikan penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk memantau perubahan perilaku siswa, dukungan psikososial berbasis sekolah, serta pendidikan literasi digital dan anti-kekerasan. Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menekankan bahwa negara wajib hadir menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak, baik di keluarga, sekolah, maupun ruang digital, melalui pengasuhan orang tua yang kuat, pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan dan toleransi, serta pengawasan konten digital yang ramah anak. BNPT juga menyiapkan program pencegahan seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, serta penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. Ancaman ideologi ekstrem yang menargetkan anak-anak Indonesia melalui ruang digital menandakan bahwa perlindungan anak dari radikalisme bukan hanya isu keamanan, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan holistik dan berkelanjutan dari seluruh komponen bangsa.